Garis-garis Kehidupan
Oleh Ardian Je
Aliran air Sungai Amu Darya, sungai
pemisah sejumlah republik di Asia Tengah, seolah mengalir di hadapan saya,
ketika saya membaca Garis Batas (Gramedia Pustaka Utama, 2011) karya travel
writer Agustinus Wibowo. Buku setebal 510 halaman itu mesti saya baca dan
nikmati dengan sabar, dengan sepenuh hati. Terkadang, saya merasa greget—ingin
mengunjungi tempat yang dideskripsikan sang penulis—saat membacanya. Ingin
rasanya memakan roti nan di Tajikistan, melihat-lihat hal luar biasa
yang terjadi di Kirgistan, berjalan di atas tumpukan salju di Kazakhstan, menggoda
wanita-wanita cantik Uzbekistan, serta berkeliling kota dengan biaya
transportasi murah di Turkmenistan. Tetapi saya mesti bersabar dan menabung
terlebih dahulu sebelum melakukan perjalanan—berkeliling Indonesia, Asia
Tenggara, dan negara-negara lainnya. Dengan perjalanan yang telah dilakukannya
di lima negara Asia Tengah itu, tentunya Agustinus telah banyak mereguk “air
kehidupan”, menjengkali garis batas-garis batas pengalaman yang terkadang menakjubkan,
terkadang pula memilukan.
Masa Lalu
Masa lalu, makhluk apakah itu?
Apakah dia hidup? Bisakah ia mati? Apakah Anda memiliki masa lalu? Apakah masa
lalu mempengaruhi masa sekarang dan masa depan?
Di
negara-negara Asia Tengah yang diarungi Agustinus Wibowo dan negara-negara baru
yang berakhiran “stan” lainnya, kebanyakan tidak dapat melepaskan diri dari
masa lalu. Negara-negara itu adalah bekas jajahan Uni Soviet (Rusia), kemudian
perlahan-lahan meraih kemerdekaannya dengan cara yang beragam. Bahasa,
arsitektur gedung, pola berpikir, masih sangat berbau Rusia, dan (sepertinya)
dengan sengaja mereka di-Rusia-kan. Orang-orang Kazakh (warga negara
Kazakhstan) sangat fasih berbahasa Rusia, bahkan lebih fasih dibandingkan
dengan orang Rusia sendiri. Bahasa Kazakhstan tidak menjadi bahasa ibu, hanya
sebagai bahasa kedua. Apartemen bergaya Rusia banyak ditemukan di Kazakhstan,
juga di negara-negara berakhiran “stan” lainnya.
Tidak
hanya bahasa, arsitektur gedung dan pola pikir saja yang seolah didoktrin pada
negara-negara bekas jajahan Uni Soviet itu, agama pun ikut digarap. Agama Islam
adalah agama mayoritas di Asia Tengah, namun ini tidak berarti bahwa umat Islam
di sana tidak meminum alkohol. Sebagai contoh, di Kirgizstan, alkohol dan vodka
adalah minuman wajib dalam setiap resepsi pernikahan (kebudayaan ini pun sangat
beraroma Rusia). Hampir seratus persen muslim di sana tidak menjalankan ibadah
puasa di bulan Ramadan. Di Tajikistan, orang-orang lebih senang mandi di “pemandian
Bibi Fatima” ketimbang bermaaf-maafan dengan sanak keluarga tercinta. Lalu
bagaimana dengan salat lima waktu? Jangankan menjalankannya, arti assalamualaikum
dan bismillahirrahmanirrahim pun mereka tak tahu.
Sepertinya,
masa lalu sangat sulit dilepaskan. Garis-garis kebudayaan dan doktrin
Rusianisme tak terelakkan, tak mudah terhapuskan oleh kemerdekaan dan
perputaran waktu, malah sebaliknya, garis-garis itu kian menebal dan berpotensi
besar untuk menjadi permanen akibat kemajuan zaman dan globalisasi.
Pemberani
Pejalan (traveler), petualang, pengelana, musafir, backpacker atau apa pun sebutan dan gelarnya, mereka adalah
pemberani, pun dengan Agustinus Wibowo. Penulis kisah perjalanan Afghanistan Selimut
Debu itu berani keluar dari garis batas negaranya, Indonesia, kemudian
memasuki garis batas Asia Tengah dengan modal uang yang tidak banyak dan niat
dan gejolak bertualang dan rasa ingin tahu yang membeludak. Beragam manusia
dari suku, agama, ras, bahasa, kebudayaan dan karakter yang berbeda ditemuinya.
Keramahtamahan bagi tamu di Tajikistan, individualisme dan keacuhan di
Kazakhstan, kebijakan negara yang aneh di Turkmenistan adalah butir-butir
pengalaman yang sulit terlupakan baginya.
Apa
yang sebenarnya Agustinus dan para pengelana lakukan? Tidakkah mereka membuang
waktu yang berharga? Mungkin salah satu jawaban yang dapat mewakili ialah:
belajar! Belajar melihat kehidupan. Belajar membaca karakter manusia dan negara
yang berbeda. Belajar kebudayaan secara langsung dengan menjadi dan terlibat dengan
pelaku budaya, masyarakat.
Hidup
sebagai pendatang atau orang asing merupakan cara terbaik memahami sebuah
lingkungan, sebuah sistem yang sedang berputar. Sering kita berpikir,
sepertinya jika kita hidup di suatu tempat berbeda kita akan menjadi lebih
baik, lebih sejahtera, bahagia, dan seterusnya. Khayalan-khayalan positif
bergelayut di pikiran. Namun belum tentu tempat yang kita impikan akan menjamin
kebahagiaan kehidupan bagi kita. Hal yang seperti demikian bersifat tak
beraturan, yang ada hanya prediksi, sekadar menebak; yang terlihat hanya
kulitnya, hanya katanya, bukan kenyataan yang hakiki.
Kembali
lagi pada perjalanan! Perjalanan, semata-mata, (juga) merupakan sebuah cara
untuk menemukan eksistensi diri, atau “Siapa aku sebenarnya?”
Setiap
orang memiliki pertanyaan tentang eksistensi dirinya, dan akan menemukan
jawabannya dengan usahanya sendiri dalam jangka waktu yang—relatif—lama, dan
cara melakukannya pun berbeda. Mungkin salah satu cara yang dapat dijalani
ialah dengan melakukan perjalanan, melewati garis batas-garis batas kehidupan
yang umum, atau memasuki garis batas-garis batas di dunia yang baru.
Apakah
Anda berani melewati garis batas “rumah” Anda, seperti yang dilakukan Agustinus
dan para pengelana lainnya?
Ardian Je, relawan Rumah
Dunia; suka sayur belut; buku puisi mutakhirnya bertajuk Bojonegara (2017).



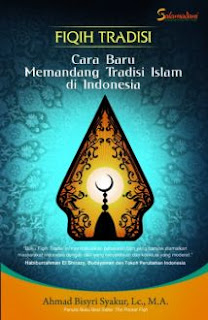

Komentar
Posting Komentar