Air Mata (Para Petani) Kopi
Oleh Ardian Je
Inspirasi untuk menulis puisi, atau karya
sastra lainnya, bisa datang dari manapun, dari apa pun, tak terkecuali kopi.
Barangkali, bagi orang biasa, kopi hanya sekadar teman "melamun" atau
teman merokok atau penambah semangat dalam berkegiatan; tetapi di mata penyair,
kopi bisa menjadi hal yang sangat berharga dan penuh makna. Aroma dan rasa kopi
bisa menjadi puisi, setidaknya itulah hal yang saya temukan dalam buku kumpulan
puisi Air Mata Kopi (Gramedia) karya Gol A Gong—berikutnya Gong.
Sebagai seorang pejalan, Gong terus mencari
kopi, mulai dari jenis, makna, hingga keresahan dan nasib para petani kopi di
Indonesia. "Perjalanan kopi", barangkali frasa inilah yang sangat
tepat dengan buku kumpulan puisi ini.
Perjalanan kopi Gong bukan sekadar perjalanan
menyinggahi kebun-kebun kopi dan kedai-kedai kopi. Lebih dari itu, perjalanan
kopi Gong adalah perjalanan kehidupan kopi. Dalam kumpulannya, pada puisi
pertama yang berjudul "Jangan Minum Kopi", Gong menyuguhkan larangan.
"Kita berdosa pada petani kopi… /Lagi pula ngopi bukan tradisi."
Mengapa Gong melarang (pembaca dan manusia
secara menyeluruh?) meminum kopi? Mungkin karena petani kopi pun tak merasakan
kesejahteraan atas nasib mereka! Barangkali jawabannya ada pada puisi yang
berjudul "Kopi Pangku": kopi diaduk kopi dipangku/ rasanya tak
sepadan dengan harga diri. Dalam puisi "Kopi Pangku" ini, ada
nada merana dari nasib para perantau—yang kebetulan menjadi "pelayan
kopi": mereka, para perantau itu, mesti rela dipangku dan disentuh-sentuh
oleh para pembeli kopi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Antara harga diri
dan keadaan ekonomi, semuanya dipertaruhkan dalam segelas kopi dan beberapa
menit pangkuan.
Tentu puisi-puisi Gong dalam kumpulan ini
menyuarakan realita dan kritik sosial, keadaan yang tengah terjadi saat ini,
dan barangkali hal ini telah terjadi dari masa lalu hingga nanti.
Mari lihat bait terakhir dari puisi yang
berjudul "Kopi Tubruk" berikut:
Aku tahu kopi tubruk kegemaranmu
dimasak mendidih sepanci airmata rakyatmu
dituang ke cangkir seng pisang rebus
bermaksud menjadi simbol kebangkitan
: cappuccino-espresso menggantikannya!
Dalam pandangan saya, di larik kedua dari
sebait puisi tersebut, jelas bahwa nasib rakyat petani kopi Indonseia tidak
sejahtera, karena kopi tubruk kegemaran (Bung Karno?) dimasak mendidih dengan
sepanci airmata rakyat Indonesia. Belum lagi pada larik terakhir cappuccino-espresso
menggantikannya!—dalam hal ini koi-kopi tradisional produksi pribumi
digantikan kopi cappuccino dan espresso, yang tidak lain adalah buatan pabrik
dan kapitalisme, yang jelas menggusur kehidupan pribumi beserta kebudayaan dan
tradisinya.
Dapat dikatakan bahwa kumpulan puisi ini,
selain bentuk perjalanan kopi sang penyair, adalah isak tangis serta kesedihan
para petani kopi. oh, pemilik biji harum kopi/ air mata kopi tumpah dari
cangkirku (puisi "Air Mata Kopi", halaman 27). Itu bisa dilihat
dengan beberapa kali munculnya frasa "air mata", bahkan frasa
tersebut digunakan dalam judul utama.
Dibalik kemelaratan para petani kopi, selain
kapitalisme, ada juga campur tangan partai politik. Politik dan kapitalisme
sulit dipisahkan, dan Gong dengan penuh kesadaran dan perasaan menuliskannya
dalam puisi yang berjudul "Di Dalam Masjid": ketika rukuk sujud
kepalaku bercabang/ melihat begitu banyak kepala kerbau/ di punggung imam dan
ma'mum.
Pandeglang, 21 Agustus 2014
Ardian Je, relawan Rumah Dunia; wartawan rumahdunia.com;
alumnus Tadris Bahasa Inggris IAIN SMH Banten. Buku puisi mutakhirnya bertajuk Bojonegara (2017).
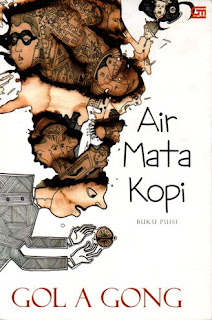


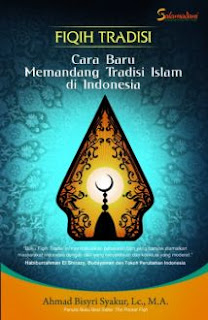

Komentar
Posting Komentar